pengajian sastra #21
digelar minggu 26 September 2010
jam satu siang
di GIM
“Menengok Sastra Sunda”
bersama :Hawe Setiawan, Dhipa Galuh Purba dan Tedi Muhtadin
pengajian sastra #21
digelar minggu 26 September 2010
jam satu siang
di GIM
“Menengok Sastra Sunda”
bersama :Hawe Setiawan, Dhipa Galuh Purba dan Tedi Muhtadin
Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »
Kehadiran Acep Zamzam Noor dan Ahda imran di Pengajian Sastra #17, Mingu 30 Mei 2010 adalah pertemuan yang indah. Kata Dedy Koral, ini pertemuan renyah dan bergizi, Semy Ikra Angara bilang ini pertemuan terindah pengajian sastra.
Tanpa berniat membawa suasana ke masa lalu dan sekedar romantisme belaka, Keduanya berkisah tentang awal-awal meraka menjadi peyair, Ahda yang datang dari seberang Sumatera bertutur bagaimana ia kesulitan melakukan kumunikasi personal dengan para seniman yang ingin ia temui karena keterbatasan teknolgi (saat itu tahun 80-an belum ada HP apalagi pesbuk), lalu Acep berkisah tentang otodidaknya menulis puisi hingga ia pergi ke Italy dan menghirup energy kepenyairan disana.
Hair pada Pengajian Sastra #17 Yopi StiaUmbara, Heri Maja Kelana, Agus Nasihin, Yanti Sri Bdiarti, Syahreza Faisal, Dian Hartati, Dedy Koral, Semi Ira Angara, Soni Farid Mulana, Moch Safari FIrdaus, Rian Ibayana, Aan Masyur dari Makasar, Kiki Merah dari Depok dll.
Setelah membacakan beberapa puisinya, Ahda san Acep mengajak para penyair muda untuk tetap memiliki ketanghuhan pola berfikir, belajar tanpa henti, banyak membaca dan mengintensifkan rasa amor pada diri.
“Penyair itu tidak mencari kata kata, tapi ia harus mampu meluruhkan dirinya pada persoalan hidup, ketika itu terjadi, maka kata kata akan datang dengan sendirinya,”ujar Ahda Imran. Sementara Acep mengatakan, kata-kata ibarat hidayah, ia akan datang pada orang yang kembali menekuni kebenaran persoalan, orang yang tidak pandai memaknai hidup dengan sendirinya ia telah kehilangan hidayah; kata kata.
Acep lagi-lagi mengulas soal teori bulu kuduk, sebuah teori yang kini menyebar ke dunia sastra. Dalam teori bulu kuduk Acep disebutkan bahwa puisi yang baik adalah puisi yang mampu ,membuat bulu kuduk berdiri. “Saya suka bingung kalau ditanya bagaimana menulis puisi yang baik, karena saya belajar puisi sendiri dan tidak punya teori, akhirnya saya bilang saja seperti, dan menjadi teori bulu kuduk” paparnya.
Acep bahkan memilki teori lain soal membuat puisi, yakni teori “Batu Akik”, Puisi itu seperti seperti batu akik, batu akik sebelum menjadi batu akik, ia adalah batu yang tak berbentuk, lalu melalui poses yang lama dan panjang maka jadilah ia batu akik yang halus, indah dan nikmat dipandang.
Pada persoalan lain Ahda Imran mengatakan, keberuntungan penyair yang hidup di zaman teknologi, lahirnya media Online menjadi bagian pertumbuhan sastra. “Yang paling penting dari semuanya itu tidak hanya media, tapi bagaimana seorang penyair mampu menyikapinya secara arif,” imbuh Ahda.
Ah euy, banyak yang yang ingin saya bagikan pada kawan-kawan di pegajian Sastra #17, tapi saya tidak mencatat semuanya, soalna saya na jadi moderator….kalau ada yang mau menambahkan, sok atuh silahkan ditambah….Cag!!
Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »
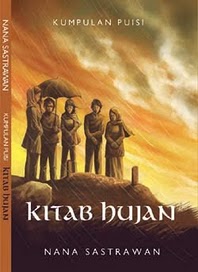 Saya belum lama mengenal Nana Sastrawan, baik sosok maupun karyanya, tapi saya mengenal semangatnya dalam berkarya. Dan untuk memberi pengantar buku puisi ini, kiranya perlu saya katakan kembali, bahwa seseorang bisa sampai pada makom sebagai penyair ketika melalui berbagai proses yang panjang.
Saya belum lama mengenal Nana Sastrawan, baik sosok maupun karyanya, tapi saya mengenal semangatnya dalam berkarya. Dan untuk memberi pengantar buku puisi ini, kiranya perlu saya katakan kembali, bahwa seseorang bisa sampai pada makom sebagai penyair ketika melalui berbagai proses yang panjang.
Antara penyair dan puisi sama-sama melalui proses. Seseorang tidak akan pernah mencapai “sesuatu” kecuali melalui enam proses, begitupun seseorang tidak pernah disebut penyair kecuali melalui enam proses, ;
Pertama, Dakain. Seseorang bisa disebut penyair jika bisa membuat puisi (tentunya), dan untuk membuat puisi ia harus Dakaain yang artinya cerdas. Orang yang tidak cerdas memahami persoalan hidup, tidak cerdas menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak cerdas mengaktualisasikan situasi yang ada, maka ia tidak mungkin bisa membuat puisi dengan baik. Penyair harus cerdas memahami berbagai persoalan sosial, pilitik, ekonomi dan budaya, kecerdasan ini akan mengalirkan kekuatan hebat pada akal pikiran dan hatinya untuk tergerak menulis puisi.
Kedua, Hirsin. Menjadi penyair harus melalui proses Hirsin (tertarik atau hobi). Seseorang mampu menulis puisi pada awalnya adalah hobi, dari hobi itulah ia akan berupaya untuk menulis. Latar belakang hobi bisa bermacam-macam, bisa berawal dari hobi menulis kata-kata indah, atau waktu di sekolah pinter merayu wanita teman sekelas, atau membuat surat pada pacar dengan menggunakan puisi sebagai medianya, atau ada juga seseorang nenulis puisi karena memang berbakat dan hobi sejati, bisa juga karena orang tersebut sering gaul dengan seniman, banyak membaca buku sastra atau sering menonton pertunjukan sastra.
Ketiga, Istibar atau sabar. Menulis bukan pekerjaan gampang, ia butuh kesabaran nabi Nuh, butuh ketalatenan Nabi Musa, perlu keberanian Nabi Ibrahim dan Ketulusan Muhammad. Menulis puisi butuh tenaga ekstra, fikiran jernih dan tahajud yang sempurna, bahkan kalau perlu butuh penelitian ilmiah, baik secara struktur estetik maupun muatan yang terkandung di dalamnya.
Keempat, Dzumallin. Menulis puisi ternyata harus Dzumalin; membutuhkan biaya yang cukup mahal. Paling tidak, proses menulis puisi diawali dengan empiris seseorang, baik empiris disengaja ataupun tidak. Empirisme terkadang membutuhkan biaya yang tinggi. yakni biaya uang, tenaga dan pikiran. Misalnya sebelum menulis puisi ia melakukan sebuah penelitian di lapangan tentang persoalan yang sedang dan akan ia tulis, dan itu membutuhkan dana yang besar. Katakan saja ia akan menulis tentang laut, sungai, pelacur, partai politik, dan lain-lain yang perlu mengeluarkan kocek untuk itu, perlu tenaga dan konsentrasi pikiran.
Kelima Irsadun. Arti sebenarnya Irsadun adalah guru atau yang mengarahkan, namun saya ingin memaknainya sebagai kritikus. Seorang penyair butuh kritikus. Sesungguhnya puisi telah mati tanpa lehadiran kritik
Keenam, Tuuli zamanin. Waktu yang panjang merupakan waktu yang dbutuhkan oleh seseorang agar tetap disebut sebagai penyair, artinya seseorang yang baru menulis satu atau dua puisi belum tentu secara tiba tiba disebut penyair, walaupun sah-sah saja ia menyebut dirinya sebagai penyair, tapi kemudian legitimasi penyair tidak ditentukan oleh diri sendiri, yang menyebut seseorang sebagai penyair adalah ummat, karya dan seleksi alam yang mengalir. Jadi, penyair tak beda dengan sebutan Ajengan, ustadz atau Kyai, ia lahir dari masyarakat yang menyebutnya demikian. Menulis puisi yang baik membutuhkan jam terbang cukup lama, jam terbang itu sendiri tidak ditentukan oleh batas waktu setahun atau dua tahun. Kata Acep Zamzam Noor, menulis puisi itu harus berdarah darah.
***
Dari keenam proses tadi, nampaknya Nana sastrawan sudah dan sedang melaluinya dengan baik, ia mampu melewati proses untuk menuju makom diri sebagai penyair. Hal ini bisa dilihat dari puisi-puisinya yang terkumpul dalam antologi Kitab Hujan. Saya melihat gairah yang cukup tinggi dalam sajak-sajaknya. Puisi bagi Nana ibarat sms yang selalu mengggangu tidurnya, kedalaman imaji dan pengolahan pikiran yang liar terdapat pada puisi berjudul “Perempuan”
Aku tenggelam dalam tubuhmu, setiap detik. Selalu
mencumbu pantai di punggungmu
gelombang pasang hilang hening sagara
sia sia dan menyerah
dst
puisi sejenis terdapat pada “Ibuku Perempuan Gila”,”Illusioner”,”Asing”
keindahan bunyi dalam puisi, dan pegolahan kata serta empirisme yang penyair
mampu membawa si pembaca memahaminya pula (dengan penilaian subyektif
masing-masing tentunya). Puisi bisa memberi kita makna yang sangat dalam ketika ditulis dengan kejujuran dan berdasar pada kehidupan yang sesungguhnya.
Simak misalnya larik kemarahan dan kekecewaan pada diri Nana di puisi “Kota, Peluh Dan Tergenang”
kami di atas rumput dengan air liur kering
mereka tertawa dengan air liur menetes
kalian terdiam dengan air liur basah
kita terinjak dengan air liur meludah
kamu ngoceh dengan air liur membuncah
aku menangis dengan air liur habis
Terlalu gagah sebenarnya kalau dikatakan puisi yang baik ibarat kapak tajam yang memecahkan kebekuan es dalam kepala kita. Tapi harus diakui, puisi yang baik selalu menggoda kita untujk membacanya berulang kali. Beberapa puisi Nana
memiliki daya tarik unsur bunyi yang indah, gagasan dan liriknya
bersenyawa, idiomnya sederhana, ada kejutan, jujur dan imaji yang lumayan seperti pada puisi “Percakapan Malam”, “Kekasih”,”Pengantin”,”Kepadamu”,Buih Sepi”.Menggoda kita untuk membaca ulang.
Sesekali Nana terjebak pada keasyikan mengakhiri setiap lariknya dengan irama yang sama, mengingatkan kita pada puisi zaman baheula, simak saja puisi berjudul “Mimpi Kamar Mandi”, dan “ Kelakar”
Pada Puisi berjudul “Perang”, Nana mencoba bermain-main dengan kata-kata, mencoba menulis puisi mbeling, namun ia gagal memaknainya sebagai puisi yang berhasil menjadi puisi yang difahami pembaca.
***
Setiap penyair memiliki wilayah perhatian tersendiri, pun pada diri Nana. Wilayah sosial, politik dan budaya menjadi bagian dari hampir semua puisinya, ia mencoba “masuk” ke dalam persoalan itu. Ada semacam protes lembut dari hampir semua puisinya dalam buku ini.
Sejumlah pengalaman batin, menggambarkan realitas hidup, penuh estetika, idiom, dan metafor ditulis secara gamblang, Ya, Nana memang tengah menulis realitas. Kematangan nalar kemudian menjadi persoalan dalam bekerja menulis puisi, karena meskipun puisi ditulis dengan rekaan kata, tapi isinya adalah realitas kata.
Selebihnya saya salut, Nana tidak bercita-cita ingin menjadi ketua Partai politik, atau anggota DPR, ia lebih menginginkan hati nya dijejali oleh berbagai pengalaman bathin yang mengendap jadi persoalan hidup (sedih, senang, marah dll).
Hanya satu proses lagi yang harus dilalui Nana, ialah memperbanyak membaca ayat-ayat kauniyah dan memelihara kontemplasi yang lebih serius.
Selamat dan tetap semangat!!
*** Matdon
Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »
MAJELIS Sastra Bandung (MSB) mulai dibuka pada 25 Januari 2009. Forum ini diprakarsai oleh penyair dan wartawan Matdon, penyair Dedy Koral, penulis dan fotografer Aendra H. Medita, penulis Hermana HMT, aktivis Hanief, aktor Ayi Kurnia, dan dramawan Yusef Muldiana. Forum tersebut berbasis di Bandung, dan menyelenggarakan pertemuan bulanan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM)—bekas gedung landraad (pengadilan pribumi) zaman kolonial .
Sejak MSB mengawali kegiatannya, setiap bulan Matdon dan kawan-kawan mengundang dua hingga empat penyair untuk menghadirkan karya masing-masing dalam forum, yang kemudian dibahas oleh hadirin. Selain biasa bertemu muka dalam forum diskusi di GIM, para peserta forum ini biasa berbagi karya dan komentar seputar sajak melalui jejaring sosial facebook. Lebih kurang setahun sejak forum ini mulai dibuka, terbit antologi puisi Ziarah Kata (Majelis Sastra Bandung, 2010).
Ziarah Kata menghimpun 99 judul sajak dari 44 orang penyair. Para penyair yang karyanya dimuat dalam buku 110 halaman ini pada umumnya pernah diundang oleh MSB ke Bandung untuk membaca puisi dan berdiskusi. Sebagian besar di antaranya lahir pada dasawarsa 1970-an hingga 1980-an. Penyair “sulung” adalah Iwan Soekri Munaf yang lahir pada 1957, sedangkan penyair “bungsu” adalah Zulkifli Songyanan yang lahir pada 1990. Sebagian besar di antaranya kini tinggal di Bandung atau wilayah di dekatnya. Beberapa di antaranya sering mengumumkan sajak melalui forum atau media lain, seperti Bode Riswandi, Dian Hartati, Ratna Ayu Budhiarti, Toni Lesmana, dan Ujianto Sadewa. Nama baru cukup banyak.
Buku ini diterbitkan oleh MSB sendiri, dan merupakan buku pertama yang dihasilkan dari forum tersebut. Menurut Matdon, “Rois ‘Am” MSB, terbitnya antologi ini dapat “mempertegas bahwa MSB serius menjadi semacam ruang tadarusan puisi”.
***
UNGKAPAN “ziarah kata” bisa mendua makna. Pertama, upaya menghikmati atau menghormati kata sedemikian rupa, seakan kata adalah hal keramat. Kedua, laku kata yang menyerupai kegiatan berziarah, dalam arti bahwa kata-kata yang muncul dalam puisi dapat menghikmati kehidupan (atau kematian) dunia manusia. Mungkin, ungkapan itu sedikit banyak menyiratkan harapan tersendiri terhadap kreativitas yang selama ini diwadahi oleh MSB. Mudah-mudahan saja, ungkapan itu tidak berarti bahwa para penyair sedang menziarahi kematian kata, atau kata-kata sedang menziarahi kematian kreativitas penyair.
Sebagaimana komentar penyair Acep Zamzam Noor dalam jilid belakang antologi ini, pokok soal (subject matter) dan gaya pengucapan yang diperlihatkan oleh para penyair dalam buku ini, sudah pasti, beragam. Keragaman membentang, mulai dari puisi yang anteng memainkan bunyi, dengan sedikit kecenderungan ke arah puisi konkret, seperti karya Dave Sky (Davit Arianto), hingga puisi yang tidak membiarkan aku liriknya dibebani kemurungan atau permenungan, seperti karya Ratna Ayu Budhiarti. Ada puisi yang memuat perasaan keagamaan, misalnya karya Willy Sastra Basoilny, ada pula puisi yang mewadahi kritik sosial, misalnya karya Arry Syakir Gifari. Beberapa penyair lainnya tampak berkecenderungan melukiskan suasana atau mencatat peristiwa. Tak ketinggalan pula puisi-puisi yang mengandung alusi terhadap tokoh dalam sejarah, misalnya karya Asep Samboja dan B.F. Syarifudin. Dengan kata lain, Ziarah Kata tak ubahnya dengan bianglala.
Tentu saja, keragaman seperti itu tidak perlu dijadikan penghalang untuk membicarakan cara kata diperlakukan dalam puisi, dengan menjadikan Ziarah Kata sebagai referensinya.
Untuk membicarakan hal itu, dapat dikemukakan dua ilustrasi sederhana. Misalkan, pertama, kita kumpulkan sejumlah besar guntingan judul berita suratkabar atau majalah. Kemudian, kita gabungkan guntingan yang satu dengan guntingan yang lain, kita deretkan, dan kita bariskan sedemikian rupa, dengan tidak memperdulikan kemungkinan atau ketidakmungkinan arti kata atau kalimat yang ditimbulkannya. Hasilnya kita muat dalam rubrik atau antologi puisi. Pastilah yang terbaca kemudian adalah sebentuk puisi abstrak yang cukup gelap.
Misalkan lagi, sebagai ilustrasi kedua, kita gunting sebuah berita suratkabar atau majalah, misalnya tentang jatuhnya sebuah pesawat terbang yang mengangkut seorang presiden beserta ibu negara dan rombongannya. Kemudian kalimat-kalimat prosais dari berita itu kita penggal-penggal ke dalam sejumlah baris layaknya penggalan larik-larik puisi, misalnya dengan menekankan tegangan antarlarik yang hendak kita timbulkan. Hasilnya kita muat dalam rubrik atau antologi puisi. Pastilah yang terbaca kemudian adalah sebentuk puisi prosais yang cukup terang.
Dengan mengajukan kedua ilustrasi itu sama sekali tidak ada maksud untuk mengatakan betapa mudahnya menulis puisi. Kedua ilustrasi itu dikemukakan semata untuk mengatakan bahwa komposisi verbal, segelap atau seterang apapun isinya, dapat atau tidak dapat disebut puisi bergantung pada cara komposisi itu dibaca atau diperlakukan. Taruh kata, komposisi verbal baik yang dibuat dari guntingan kepala berita (headlines) maupun yang dibuat dari guntingan kisah berita (news story) tadi dimuat dalam rubrik puisi koran minggu. Pastilah pembaca akan memperlakukan komposisi-komposisi itu berdasarkan konvensi pembacaan puisi: misalnya bahwa suara si aku lirik mengacu pada situasi ujaran yang dibayangkan dan tidak perlu si aku lirik diidentikkan dengan penyair yang membuat komposisi itu; bahwa setiap kata, mulai dari judul hingga larik terakhir, membentuk suatu keseluruhan; bahwa dalam komposisi itu terdapat suatu pokok soal yang ditekankan; dan seterusnya.
Dari sudut kepentingan penyair sendiri, sudah tentu, ada upaya untuk menjadikan komposisi yang dibuatnya dapat diperlakukan sebagaimana layaknya puisi diperlakukan. Karena itu, pada dasarnya, ia pun membuat puisi dengan memperhatikan konvensi pembacaan puisi pula. Betapapun, saya sendiri berpendirian bahwa hal terpenting bukanlah apakah komposisi yang dibuat oleh penulis dapat atau tidak dapat disebut puisi, dan apakah penulis itu dapat atau tidak dapat disebut penyair. Hal terpenting, pada hemat saya, adalah sejauh mana penulis memperlakukan kata dalam komposisinya. Dengan kata lain, menghadirkan puisi dalam antologi bukanlah segalanya.
***
DENGAN segala hormat, sekadar untuk melangsungkan diskusi, perkenankan saya memetik salah satu puisi dari antologi ini:
Tubuh Yang Menjadi Gelombang
Kau akan menggulung lengan baju ketika hitam gelombang
merayap dari ujung-ujung jari. Sejenis selamat datang dengan
pecahan yang saling mencari. Apakah kau keping dari
ketidakberlangsungan keberadaan?
Seorang membasuh tangan
tapi sesuatu tidak terhapus dan riak air mengaduh oleh pekat
yang bergerak di permukaan. Suara-suara. Gelombang
menghantarkan pesan dari seorang yang terbenam ketika
tubuhnya terbungkus oleh manis keterhapusan. Memuai pada
hijau dasar laut. Lalu terhampar sisa percakapan yang tidak
pernah selesai. Mematung pada keabadian
Suara yang terdengar dalam puisi ini berasal dari seseorang yang berbicara kepada pembaca secara langsung, seperti dalam keadaan bersitatap. Pembaca dikondisikan untuk menjadi “kau”, dan membayangkan situasi diri ketika ujaran terhadapnya disampaikan. Hal yang dapat dibayangkan antara lain berupa permukaan laut dan dasarnya yang hijau, dan sesosok diri yang menggulung lengan baju dan mencelupkan jari-jarinya ke dalam air, hingga timbul riak-riak gelombang. Penggalan larik-larik puisi ini pun dibuat mengalun, memanjang, dan memang seperti gelombang. Terasa nikmat, sebetulnya, jika kita membaca baris-baris seperti itu, seperti yang dapat kita rasakan manakala kita terapung di atas sampan. Akan tetapi, lebih dari sekali alunan citraan itu seakan terbentur frase-frase abstrak dari kecenderungan berfilsafat: “apakah kau keping dari ketidakberlangsungan keberadaan?”; tubuh yang “terbungkus oleh manis keterhapusan”; juga tindak “mematung pada keabadian”. Selain itu, sudut pandang orang kedua yang menghasilkan lukisan situasi diri pada larik-larik awal, seakan tiba-tiba meloncat ke sudut pandang orang ketiga ketika aku lirik menggambarkan “seorang membasuh tangan…” Tidak mustahil pembaca sukar membayangkan “seorang yang membasuh tangan” (di permukaan gelombang?) sekaligus “seseorang yang terbenam”. (Ataukah ada dua orang yang sedang dibayangkan?). Siapa pula yang “mematung pada keabadian”? Kesukaran membaca juga timbul dari imaji-imaji yang seakan bertumpuk seperti “riak air mengaduh” atau “sisa percakapan” yang “terhampar”. Akhirnya, tidak mustahil, pembaca luput dari signifikansi pokok soal yang diangkat dalam puisi ini.
Kiranya, seperti itulah keadaannya apabila poetic persona cenderung dibebani oleh permenungan. Kata-kata yang dibuat memberat, dalam bentuk pasangan kata yang cenderung abstrak, bukan tidak mungkin malah mengganggu baris-baris sarat majas yang mendahului dan mengikutinya.
Permenungan itu sendiri, tentu saja, penting, tak terkecuali untuk diwadahi dalam puisi. Namun, ada kalanya permenungan itu justru tak tersampaikan sepenuhnya manakala kata-kata yang diandalkan untuk menghantarkan atau mewadahinya tampak seperti menjauh dari pengalaman konkret, dalam arti pengalaman yang dapat dibayangkan oleh manusia dalam hidup sehari-hari. Bukankah para sufi sendiri pada gilirannya mengandalkan idiom-idiom seperti “bulbul” dan “mawar” atau “cawan” dan “anggur”?
Pada titik ekstrem lainnya, permenungan penyair dibuat sedemikian gamblang, seperti dalam puisi berikut ini:
Di Angkutan Umum
Begitu angkuhnya kita
Bahkan mengalahkan keangkuhan
Para raja dan pujangga
Tak ada sapa tegur
Hanya mata yang berbicara
Yang diam-diam curi mencuri pandang
Mungkin juga saling curiga
Atau banding membandingkan
Seperti benda-benda di museum
Atau pameran
Di dalam angkutan umum
Kita seperti bukan manusia
Kita seperti bukan saudara
Sajak di atas jelas mempersoalkan ironi kebersamaan di lingkungan urban tempat interaksi justru tidak menimbulkan komunikasi. Dengan menggambarkan perilaku kolektif dalam angkutan umum, aku lirik menyesali, bahkan menggugat, kenyataan yang menunjukkan betapa orang hadir bersama tapi tidak bertegur sapa, seakan-akan mereka tidak mengenal persaudaraan di antara sesama manusia. Dalam hal menangkap gejala yang hendak diangkat sebagai pokok soal dalam sajak, kiranya sang penyair amat peka. Suasana sosial dalam angkutan umum memang representatif untuk dijadikan jendela amatan terhadap mendangkalnya kebersamaan. Hanya, barangkali, efek puitiknya yang terasa tak sempat terpikirkan sepenuhnya. Padahal, kiranya, efek itu mungkin tercapai sekiranya deskripsi tentang “keangkuhan”, “saling curiga”, atau “banding membandingkan” dicarikan gambaran konkretnya. Mungkin juga efek itu akan lebih kuat jika sedikit rasa humor dibubuhkan ke dalam ironi yang hendak digambarkan. Upaya-upaya seperti itu, kiranya, juga dapat mengatasi kemungkinan bertambahnya beban permenungan oleh kemurungan—meski, tentu saja, tidak ada yang salah dengan kemurungan.
Jangan-jangan, beban-beban seperti itu amat terpaut pada cara penyair berbicara, yang tentu saja menyiratkan caranya menyikapi persoalan yang hendak diangkat ke dalam sajak. Dalam puisi lain yang akan dikutip di bawah ini, kita dapatkan contoh yang kiranya cukup baik sehubungan dengan puisi yang dibuat supaya tidak jadi berat tapi tidak sampai luput dari potensinya untuk mewadahi kompleksitas pengalaman manusiawi. Baik kita kutip:
Pamit
Permisi…numpang tanya,
Dimana ya rasa yang kausimpan untukku dulu?
Aku lupa,
Barangkali kau ingat kapan terakhir kali
Kau hidangkan senyum termanismu
Di meja makan kita?
Hmmm…maaf ya,
Aku tidak bisa lama-lama bersama kamu
Mudah-mudahan tak keberatan jika esok lusa
Kau temukan secuil rasa yang tersisa,
Aku memintanya kembali
Untuk dihanyutkan ke sungai
Biarlah air yang menemani kenangan itu menuju laut
Sudah ya, aku pergi!
Calon suamiku sudah menunggu.
Sampai jumpa lain waktu.
***
Demikianlah sekelumit bahan perbincangan sehubungan dengan terbitnya Ziarah Kata. Di balik komentar ini terkandung harapan akan tercapainya puisi-puisi yang jauh lebih baik setelah Ziarah Kata kelak. Mohon maaf atas segala kekurangan komentar ini. Tiada sedikitpun maksud menggurui atau sok tahu. Selamat berkarya.
*****
Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »
PERTEMUAN saya dengan Ari Syakir adalah sekaligus perkenalan saya dengan Chico Mendez, seperti mengemuka dalam sajaknya yang pertama “Epitaf Untuk Chico Mendez”. Saya merasa tidak perlu malu untuk mengatakan bahwa saya sebelumnya saya belum pernah mengenal nama Chico Mendez, sehingga saya harus merasa perlu mencarinya di mesin pencari Gooegle. Setelah membaca dan memiliki sejumlah referensi tentang Chico Mendez barulah saya merasa leluasa memasuki sajak sajak itu.
Sajak “Epitaf Untuk Chico Mendez” dibuka dengan sebuah bait yang dipenuhi oleh metafora dan imaji alam menarik, yang membawa ingatan pada ruang kematian, misteri alam, perjuangan, dan hidup; Menyebrang langit/ Mencari makam yang ditanami pohon akasia/Sepanjang jalan yang meliuk-liuk/Sepanjang jalan membentur luka
Bait ini terasa kuat menyuguhkan eksplorasi bahasa pengucapan yang bertumpu pada imaji. Bait ini dengan menarik menjadi ajakan untuk memasuki jejak spirit seorang pejuang aktivis lingkungan seperti Chico Mendez; Aku mengendus bau wewangian/ Pada pengembaraan yang jaraknya berhenti di titik cahaya
Aroma perlawanan dalam sajak ini, mengikuti biografi Chico Mendez yang tewas ditembak pada 22 Desember 1988, hadir sayup-sayup. Bahkan mungkin bukan perlawanan, tapi semacam sebuah pernyataan ihwal keyakinan; “jangan ada yang mau tunduk pada uang,/ uang hanya bisa dipegang sesaat,/uang hanya bisa membuat kita /waspada/Sedang pohon-pohon ini tumbuh/ ratusan tahun./Mampukah mengganti nafas selama ratusan tahun pula./untuk jutaan manusia?”
Lewat sajak ini Ari Syakir tak hanya berangkat dari kisah tragis seorang Chico Mendez. Melainkan menyaran pada kesadaran yang dipungutnya dari sosok keteguhan aktivis lingkungan itu. Kesadaran ihwal alam, manusia, dan keyakinan di tengah hasrat-hasrat yang serba pragmatis. Dan keyakinan inilah yang jejaknya terasa terus hadir di tengah ancaman kematian. Ari tampaknya tidak tergoda untuk menatap Chico Mendez dari konteks kuasa para pemilik modal yang leluasa menyingkirkan siapapun yang menghalanginya, sehingga, misalnya, sajak ini menjadi sajak protes yang penuh perlawanan. Ia terkesan hanya mencatat jejak dari nasib tragis yang menimpa Chico Mendez, termasuk ketika menyebut Chico sebagai yang …terlalu asyik berdialog dengan hutan/Melempar batu-batu bagi para penyamun/ Sedang tumbal menunggumu /Dari jagal yang dihidupi/ Akar-akar meninabobokanmu selamanya.
Meski saya dibingungkan oleh frasa seperti malaikat anestetis atau diksi balabad, tapi pertemuan saya dengan sajak pertama Ari Syakir membuat saya tergoda untuk bertemu dengan 9 sajak berikutnya. Tapi setelah saya bertemu dengan kesembilan sajak itu, saya merasa bahwa pertemuan saya dengan sajak pertama “Epitaf Untuk Chico Mendez” adalah pertemuan yang paling menyenangkan, atau mungkin dengan sajak kedua “Sepanjang Insomnia, Aku Mengintipmu”.
Pada sajak “Sepanjang Insomnia, Aku Mengintipmu”, kembali saya bertemu dengan bait awal yang menarik; Aku mengintipmu lagi/Lewat aroma rokok/Yang sama-sama kita icip/Pada ujung batang putih langsing
Dalam bait ini eksplorasi bahasa dipungut dari gerak dan gejala keseharian, dari adegan remeh-temeh, yang merepsesentasikan suasana persajakan. Ada jarak antara Aku lirik dan sesuatu yang dihasratkannya, meski keduanya berada dalam ruang yang sama, yakni, di ujung batang putih langsing. Sajak ini dengan baik merepsentasikan hasrat yang sayup-sayup, pertemuan di ruang yang sama namun sekaligus tak bisa saling menjamah. Akhirnya, Aku lirik dan hasratnya hanya memiliki celah untuk mengintip. Sebuah gerak atau tindakan yang diam-diam. Meski lagi-lagi saya tertarung pada diksi yang samar bahkan cenderung menggelapkan—“ruang seduh”—tapi secara keseluruhan sajak ini mengemuka dalam keutuhan pengucapannya. Ada kontrol yang ketat dalam setiap bangun imaji dan metafornya.
Tapi ternyata hanya sampai di situ pertemuan saya dengan Ary Syakir. Peremuan saya dengan delapan sajaknya yang lain membuat saya tertarung-tarung. Jika dalam dua sajaknya yang pertama ada upaya untuk mengontrol pengucapan dalam membangun metafora dan kesadaran; pada delapan sajak lainnya pengucapan begitu verbal dengan lanskap tema-tema sosial-politik yang dibebani aktualitas; Mata uang memberangus/Mulut-mulut binatang buas yang berpatroli/Mengelilingi rimbun pohon jagat raya/Membagi ke saku celana dimana para komisi/Serasa mendapat BLT dari limpahan pengusaha//…// O, hutang kelahiran/Dalam dada jagat raya/Udara akan segera di-PHK/Sisanya bekerja terbata-bata (“Hutan”)
Dibandingkan dengan sajak “Epitaf Untuk Chico Mendez”, betapa berbedanya pengucapan Ary Syakir dalam sajak ini. Demikian pula sejumlah sajaknya yang lain. Bahasa di situ seolah tak pernah dibiarkan menjadi subjek otonom, melainkan diberi tugas untuk menyuarakan tema dan gagasan, sehingga nyaris puisi hanya bisa dimasuki dari satu pintu, dan menutup pintu-pintu lainnya, sebutlah sajak “Lawamah Dunya’” atau “Mujahid Bukan Hanya Milik Mereka Yang Berdarah”.
Tampaknya dalam delapan sajak ini Ary mulai mencoba mengajak saya memasuki tema-tema “besar”, tentang Tuhan, para nabi, atau tentang sensualitas yang ingin berkesan menjadi liar. Pertemuan saya dengan delapan sajak Ary ini adalah pertemuan dengan tarik-menarik antara bentuk dan isi. Terasa benar berbagai upaya dilakukan agar bentuk pengucapan bisa leluasa mengusung gagasan. Dari mulai bentuk tipografi hingga keliaran yang terasa dipaksakan. Akibatnya sajak jadi cenderung verbal, bertumpuk, dan gelap.
Tapi seandainya delapan sajak ini merupakan bentuk eksperimen atau semacam pencarian untuk menemukan berbagai kemungkinan, saya tidak menyesali pertemuan saya dengan delapan sajak tersebut, sembari tetap mengatakan bahwa pertemuan saya dengan “Epitaf Untuk Chico Mendez” dan “Sepanjang Insomnia, Aku Mengintipmu” adalah dua pertemuan yang paling menyenangkan.
**
PERTEMUAN saya dengan sajak-sajak Johan Khirul Zaman membawa saya pada berbagai kesadaran tentang perjuangan manusia menegakkan kebenaran dan kemuliaan di tengah realitas. Dengan bahasa yang cair Johan mempertemukan saya dengan berbagai gugatan dan fatwa-fatwa sosial; Jangan kau tanya kecintaanku pada bangsa ini/ tapi tanyakan berapa banyak orang yang rela/ menjual kekayaan bangsa ini (“Jangan”); oh….politikus rakus yang telah membanjiri bumi/ sampai kapan kau rampas mimpi menjadi tragedi? (“Justice for All”); saat perempuan dipaksa/ melayani mesin-mesin pabrik/ sedang ekonom, seniman, budayawan, diajak berdansa/ di panggung sirkus para politikus. (“Sampah, Perempuan, Rindu dan Hilang”).
Keadilan yang tidak adil, ayat-ayat Tuhan yang menjadi industri hiburan, kemunafikan, manusia yang tanpa keyakinan, perempuan yang dijual, budaya urban yang menawarkan mimpi, demokrasi yang tidak menawarkan kesejahteraan, dan berbagai realitas lain yang semuanya berengsek. Begitulah dunia yang saya temui dalam sajak-sajak Johan Khirul Zaman. Nyaris seluruh sajak-sajak Johan mengambil tema potret sosial dan kehidupan manusia Indonesia. Potret dunia ketiga yang karut-marut.
Kecuali dalam “Pusaka Sunyi Seorang Pejuang”, alih-alih Johan Khirul Zaman mengajak saya masuk lebih jauh ke dalam realitas dunia yang diusungnya, sajak-sajak Johan lebih terkesan membuat saya diposisikan sebagai seseorang yang mendengar begitu banyak gerutuan. Realitas yang diungkap hadir dalam irama persajakan yang menggerutu, dengan memposisikan Aku lirik sebagai penyuara kebenaran, di tengah berbegai keputus-asaan.
Puisi memang reaksi atas sebuah keadaan. Demikian pula sajak-sajak Johan Khirul Zaman. Hanya saja soalnya bagaimana reaksi itu dinyatakan. Inilah soalnya, di sini lagi-lagi saya bertemu dengan nasib bahasa yang hanya menjadi alat atau kendaraan untuk menyuarakan gagasan. Pertarungan Johan dengan bentuk dan isi memang amat terasa dalam sajak-sajaknya. Keinginan untuk mengungkapkan berbagai kesadaran seringkali membuat bahasa kehilangan kontrolnya, sehingga cenderung menjadi tumpang-tindih. Lihat, misalnya, dua baris awal dalam sajak “Pusaka Sunyi Seorang Pejuang”; Jikalau tiba penabur datang kembali/esok pastilah tiba sejatinya
Bagaimana sebenarnya saya harus masuk ke dalam dua baris yang diungkapkan dalam satu nafas ini di hadapan pemaknaan kata “tiba” dan “datang”? Dua bait ini awal sudah membuat saya tertarung karena saya merasa Johan tidak efektif dan fasih menggunakan perangkat puitiknya.
Tampaknya Johan sangat berhasrat untuk merepresentasikan seluruh realitas dunia yang berengsek di sekeliling kita. Tema-tema sajaknya banyak berfokus pada hal-hal tersebut. Tentu saja menarik mengusung tema-tema sosial yang mudah ditemukan konteks dan aktualitasnya. Hanya saja, di tataran bentuk terasa gagasan di dalamnya masih mengambang di permukaan, meski sudut kesadaran yang direpresentasikan Johan lumayan menarik. Sebutlah sajak “Jangan”. Permainan ungkapan dalam sajak ini menciptakan irama persajakan yang dinamis, yang pulang-pergi antara yang ideal (das sollen) dan das sein (yang nyata).
Barangkali karena hasrat untuk mengungkapkan realitas dunia yang serba berengsek inilah yang membuat tidak bisa mengontrol pengucapannya, sehingga pengucapannya menjadi boros dan tidak efektif. Ada selalu frasa-frasa yang menarik namun kemudian tertimbun oleh diksi atau imaji berikutnya yang sesungguhnya tidak perlu. Sebutlah, jangan kau tanya seberapa kuat /imanku pada Tuhan/ tapi tanyalah berapa banyak yang menjual ayat-ayat Tuhan/ demi kekuasaan dan kelicikan (“Jangan”). Deskripsi “demi kekuasaan dan kelicikan” sebenarnya tidaklah begitu diperlukan, seandainya pun tidak ada, dua baris sebelumnya telah menjadi ungkapan yang utuh.
**
PERTEMUAN saya dengan Restu Ashari Putra adalah pertemuan dengan semacam janji, bahwa di kemudian hari sajak-sajaknya bukan melulu sekadar sketsa. Ya, pertemuan saya dengan sajak-sajak Restu adalah perjumpaan dengan berbagai sketsa, baik pilihan tematik mau pun gagasan yang menyaran di baliknya.
Tapi demikian, meski hanya sketsa, Restu juga menjanjikan semacam pendalaman atas tema-tema yang diusungnya. Umumnya sajak-sajak Restu menating dunia eksistensi manusia dalam ruang keseharian. Sajak-sajaknya membawa saya untuk bertemu dengan berbagai metafora yang segar; seperti cinta menghangatkan air dalam termos (“Weekend”); kau hampir saja memeluk tuhan (Air mata Sang Pujangga); kehidupan itu sekarang, selokan pipa/ ke pipa-pipa (“Kepada Pilihan”).
Sketsa dalam sajak-sajak Restu adalah sketsa ruang persajakan yang sebenarnya berpotensi menampilkan kejernihan bahasa. Tampaknya Restu tidak terpikat untuk mengekspolorasi bahasa lebih jauh, bahasa dan ungkapannya ekonomis. Ada upaya untuk memadatkan ungkapan tanpa tergoda untuk menariknya lebih jauh ke dalam pengembaraan imajinasi. Ia cenderung menampilkan metafora-metafora singkat, dengan citraan dunia keseharian.
Hanya saja sejak puisi pertama “Riwayat” saya sudah terantuk pada frasa gelap yang mengaburkan sketsa yang dibangun Restu; masih ada yang menyelinap/mengintip waktu lantas bersenggama buku/menelisik di setiap halaman. Entah dengan pemaknaan bagaimana saya bisa berinteraksi dengan frasa “bersenggama buku” pada baris kedua itu. Diksi buku mungkin bisa ditarik ke dalam berbagai personifikasi ihwal perjalanan hidup atau dunia. Tapi ketika ia menjadi frasa “bersenggama buku” di tengah ungkapan yang demikian jernih, frasa itu jadi membuat keruh seluruh bangun pengucapan.
Sajak-sajak Restu juga menghidangkan permenungan di hadapan realitas keseharian. Karena itu sajak-sajaknya cenderung tidak banyak bergerak, melainkan diam di suatu tempat. Seolah-olah proses penulisan sajak Restu adalah begini: duduk, melihat sesuatu, merenungkannya, lalu menulis. Dan yang menarik paling, dalam puisi Restu bait akhir selalu hadir sebagai semacam kesimpulan penutup atas permenungannya, misalnya sajak, “Riwayat”, “Weekend”, atau “Air Mata Pujangga”.
Saya sebenarnya diam-diam menyimpan semacam harapan, bahwa pertemuan saya dengan sajak-sajak Restu berikutnya bukanlah pertemuan dengan berbagai sketsa. Restu telah menjanjikannya dengan eksplorasi bahasa yang jernih, hanya soalnya bagaimana ia berupaya membuat sajaknya lebih bergerak jauh ke dalam tema, menjelajahi berbagai kemungkinan yang tidak melulu hanya sebatas sebuah sketsa.
**
PERTEMUAN saya denga sajak-sajak Semmy Ikra Anggara adalah pertemuan yang kesekian kalinya, setelah saya cukup sering saya bertemu dengan sejumlah karyanya yang dikirim ke meja redaksi Khazanah. Seperti pertemuan langsung dalam berbagai percakapan, saya tidak beranjak dari pendapat saya pada sajak-sajak Semmy, bahwa saya tidak pernah tertarik bertemu dengan sajak-sajak Semmy yang mengambil tema-tema besar. Bukan berarti sajak Semmy dengan tema semacam itu jelek, tapi sajaknya yang bertemakan keseharian terasa membawa saya ke ruang pendalaman yang intens, bahkan kadang mengejutkan.
Tapi tidak dengan sajak-sajak seperti “Di Gaza Tahun Berganti”. Sajak ini sebenarnya menarik, bertutur ihwal situasi yang mengerikan di Jalur Gaza. Sajak ini jelas berangkat dari konteks faktual yang terjadi ketika Israel mengepung dan menggempur Gaza. Demikian pula bangun pengucapan Semmy. Ia melukiskan mimpi, kepolosan, sekaligus ketakutan. Hanya saja persoalannya kita, paling tidak saya, tetap merasa terjarak dengan kengerian yang diungkapkan Semmy. Saya tetap merasa ngeri menyaksikan Gaza di televisi ketimbang membaca sajak Semmy yang mengalihkan Gaza ke dalam teks puisi dari sebuah jarak empiris yang berlainan.
Meski begitu, lewat sajak ini saya bertemu dengan kefasihan Semmy mengolah perangkat puitiknya. Demikian pula gagasan kesadaran yang terasa diucapkan dengan tegas. Semmy tampaknya tidak tertarik pada metafora-metafora yang mendayu-dayu dan cenderung menjadi klise. Kita misalnya bisa membaca sajaknya “Beternak Penyair”. Sajaknya ini mengapungkan sikap paradi sekaligus sinisme terhadap generasi kepenyairan. Membaca nama Acep seraya memiliki referensi tentang biografi kepenyairan Semmy di Sanggar Sastra Tasikmalaya, kita tergoda untuk mengaitkannya dengan nama Acep Zamzam Noor dan SST.
Dengan meminjam prosesi para peternak ikan, koperasi desa, dan palawija, Semmy memandang generasi kepenyairan. Di sini dengan ringan, jenaka, dan sinis, Semmy meneropong bagaimana generasi kepenyairan itu berlangsung.
Sajak-sajak Semmy hadir dengan banyak tema dengan style pengucapan yang kerapkali tak terduga; Namun cinta juga telah kusimpan hanya untuk diriku sendiri/Kecuali kau mau menyerahkan wajahmu yang lain/Inilah pisau kepunyaan ibuku/Tahanlah kesakitanmu, akan kukuliti wajahmu. (Inilah wajahku); Pada layar komputerku/ Tersimpan sepotong gigi penari (Puisi yang Pandai Menyanyi).
Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »
Sebuah sajak konon suka merintih, dan tergetar. Si penyair merintih dan tergetar kepada hari-hari dan persitiwa, atau pemikiran, atau lainnya. Tapi, ia bukan cuma merintih. Ia juga bisa berdoa, dengan kata-kata terang dan terbuka..
Nandang R.Pamungkas, misalnya. Ia merintih pada Kartu Pos. Ia membuat rintihannya bukan hanya sekadar keluh, atau sentimentil. Kepada “hujan”, dalam sajak Kartu Pos buat Teman 2, ia merintih pada “rindu / telaga ibu”. Dan, merasakan rintihannya “dalam dimensi / yang paling asing”.
Kartu Pos menjadi alat Nandang bertemu ibu: sosok wanita yang menyimpun ngilu tersendiri, bagi lelaki yang telah dimakan waktu dan banyak peristiwa: dan pengalaman. “Telaga” pun masuk ke dalam Kartu Pos. Ibu menjadi “dimensi “, menjadi “asing” : Menjadi rintihan pada banyak peristiwa hidup yang ditemuinya.
Rintihan Kartu Pos-nya juga berisi tentang “anakku” yang sedang “ belajar membaca” (sajak Kartu Pos buat Razita). Ia meminta “bacalah / walau hanya seekor katak / yang meloncat / ke tengah kolam.” Belajar tidak meremehkan “seekor katak”.Ia ingin anaknya membaca cara “meloncat” ke dalam “kolam” kehidupan.
Semua itu terjadi di dalam Kartu Pos.
Nandang juga tergetar pada hal-hal yang kerap dilupakan orang. Getarannya masuk ke dalam Lampu Pijar, misalnya: yang membuat “bayang / di dinding kamar / yang … terbakar”. Bahkan, menyihir “waktu / menjadi batu”. Ia melihat peristiwa Semadi yang membuat “lumut …di kepala” pertapa “menjadi / helai-helai rambut ular”. Ia mendengar “angin” / membisiki daun / pelan-pelan” (Tentang Daun). Ia merasakan saat Hujan Telah Reda: “jalanan basah / terbujur kaku / memanjang”. Dan, “dari setaman bunga … di halaman”, ia melihat bulan “desember / telah memberiku / sekuntum keyakinan” (Taman Bunga dan Desember).
Tapi, sebuah sajak bisa juga seperti orang berdoa, yang terang dan terbuka.
Wong Agung Utomo menorehkan yang dipikirkannya ke dalam sajak. Di angkutan umum, ia menolak “kita / seperti bukan manusia …/ bukan saudara”. Ia mengartikan “pulang” sebagai “mimpi / tak mudah dimengerti … / tak harus dimengerti” (Bagi sebagian kita). Ia merasa “menikmati perempuan / hanya pegal-pegal / di badan (Membicarakan perempuan). Ia meminta “masa lalu” janganlah sekadar “menikamkan / pilu” (Masalalu terkadang). Kenangan merupakan “segumpal abu” yang “dibakar / waktu”, dan “diterbangkan / cerita” tapi tetap “melekat”.
Doa-doa Utomo memang terasa plastis di dalam sajak. Ia memilih jalan terang, dan terbuka, dan sedikit metafora. Ia memilih judul sajak Tiada guna mengeluh, untuk memaknai “hidup” sebagai “kelelahan / dan kekalahan / yang panjang / mengekang”. Dan, memilih judul Di dinding naraka, dengan enteng. Dan, tanpa jeda, mengajak pembaca langsung melihat “lantainya” juga. Di sana, ada yang “ ingin kutuliskan kepada “ Tuhan” bahwa “Aku / Bukan nabimu”.
Saya beruntung disuruh Matdon, mengulas sajak-sajak Nandang R.Pamungkas dan Wong Agung Utomo. Sebagai peminat puisi yang tak begitu baik, saya disuruh mengenali apa arti sajak. Ada kata. Ada Makna. Ada upaya.
Saya tak begitu paham seluk-beluk sajak. Tapi, dari suruhan Matdon ini, saya mengenali kata, makna, dan upaya penyair mengenali kehidupan.
Bandung 14 Juni 2009
Disampaikan pada Pengajian Sastra – Majelis Sastra Bandung yang dipimpin Rois ‘Am Kia puisi Bandung, Matdon
Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »
oleh : Soni Farid Maulana
KEGIATAN sastra yang dilakukan oleh komunitas-komunitas sastra di atas pada dasarnya lebih kepada acara mengundang orang untuk baca puisi, diskusi, dan menerbitkan buku. Sedangkan kegiatan yang membicarakan lahirnya kemungkinan daya estetik baru dalam penulisan karya sastra boleh dibilang tidak tersentuh.
TUMBUH dan berkembangnya gerakan puisi mBeling di Bandung, yang digagas oleh penyair Jeihan Sukmantoro dan Remy Sylado pada awal 1970-an, merupakan reaksi atas digelarnya Perkemahan Kaum Urakan yang diprakarsai penyair sekaligus teaterawan Rendra bersama Bengkel Teater Rendra pada 16 Oktober 1971, di Pantai Parangtritis, Yogyakarta.
Lahirnya gerakan puisi mBeling dalam konteks yang demikian pada satu sisi menunjukkan sebuah semangat pencarian baru dalam bentuk pengucapan puisi, yang pada saat itu bentuk pengucapan puisi liris mulai mendapat tempat yang tak tergoyahkan di majalah sastra Horison, Basis, dan Budaya Jaya.
Tentu saja gerakan yang mengejutkan dari Bandung pada 1970-an, bukan hanya itu. Ada juga gerakan lainnya yang bikin marah penyair Goenawan Mohamad dan Sapardi Djoko Damono. Gerakan tersebut adalah, digelarnya acara Pengadilan Puisi pada 1974, dengan tokohnya antara lain penyair Sutardji Calzoum Bachri, Slamet Sukirnanto, dan Darmanto Jatman.
Adapun yang menyebabkan Goenawan dan Sapardi marah antara lain atas kritik penyair Slamet Sukirnanto terhadap majalah sastra Horison, dengan tuduhan bahwa majalah sastra Horison mengembangbiakkan puisi lirik secara berlebihan sehingga tidak memberi tempat bagi munculnya kemungkinan-kemungkinan baru dalam pengucapan puisi Indonesia modern.
Puisi lirik yang dimaksud Slamet Sukirnanto dalam tulisannya itu adalah puisi yang dikembangkan penyair Goenawan Mohamad dan Sapardi Djoko Damono, yang hingga kini tumbuh dengan amat suburnya. Cabang dari gaya penulisan lirik ini, antara lain saat ini bisa kita lihat pada puisi Acep Zamzam Noor, murid terkasih penyair Saini K.M. dari pondok pesantren Pertemuan Kecil.
Penulisan puisi yang dikembangkan Sutardji Calzoum Bachri dan Darmanto Jatman pada saat itu, boleh dibilang merupakan warna baru juga. Sutardji lebih mengoptimalkan kata beda, keterangan, dan kata sifat dalam puisi-puisinya yang mengangkat mantra sebagai roh bagi daya ekspresinya, yang kemudian dikukuhkannya lewat credo puisi yang ditulisnya. Sedangkan Damanto Jatman mencoba lain, yakni memasukkan kosakata bahasa Jawa dan bahasa asing dalam puisi-puisinya yang semi naratif, yang pada awal-awal perkembangannya ditolak publikasinya oleh majalah sastra Horison.
Lantas bagaimana perkembangan dan pertumbuhan puisi di Bandung sebelum 1970-an? Nyaris sezaman dengan penyair Chairil Anwar di Bandung saat itu ada penyair Rustandi Kartakusumah, setelah itu sezaman dengan Ajip Rosidi di Bandung ada penyair Toto Sudarto S. Bachtiar, Ramadhan KH dan Dodong Djiwapradja. Sedangkan Saini KM mulai malang melintang pada 1960-an setelah diberi kepercayaan mengelola rubrik puisi di lembaran Kuntum Mekar, yakni lembaran yang terbit setiap Minggu di HU Pikiran Rakyat periode awal.
Sebagaimana dikatakan Saini KM dalam percakapannya dengan penulis, bahwa periode Kuntum Mekar, melahirkan pula sejumlah penyair yang tidak bisa dianggap enteng. Paling tidak hal itu bisa kita lihat jejaknya pada kepenyairan Sanento Juliman dan Yuswaldi Salya. Kuntum Mekar yang tutup pada akhir 1965 itu, untuk sementara waktu menyebabkan dunia tulis-menulis puisi di media massa cetak, khususnya di HU Pikiran Rakyat terhenti.
Baru pada 1976, setelah sekian tahun HU Pikiran Rakyat tumbuh dan berkembang dalam manajemen yang baru, Saini KM kembali mengelola rubrik puisi yang diberi nama Pertemuan Kecil. Dari pondok pesantren Pertemuan Kecil lahirlah sejumlah penyair yang malang melintang. Mereka antara lain, Yessi Anwar, Juniarso Ridwan, Moel Mge, Beni Setia, Giyarno Emha, Acep Zamzam Noor, Agus R. Sardjono, Nirwan Dewanto, Nenden Lilis Aisyah, Beni R. Budiman, Cecep Syamsul Hari hingga Ahda Imran, dan sejumlah nama lainnya.
Lepas dari itu, pada awal 1980-an di Bandung, penyair Diro Aritonang dan Yessi Anwar mendirikan komunitas Kerabat Pengarang Bandung (KPB) yang bermarkas di Gedung Kesenian Rumentang Siang. Komunitas ini selain menyelenggarakan berbagai kegiatan sastra seperti baca puisi dan lomba baca puisi, juga menyelenggarakan diskusi sastra. Pada 1985 Kerabat Pengarang Bandung bermetamorfosis jadi Kelompok Sepuluh yang dikomandani Mohamad Ridlo E’isy. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini nyaris sama. Bedanya, acara-acara diskusi yang digelar tidak hanya melulu karya sastra, tetapi juga membahas masalah politik, hukum, agama, dan masalah-masalah sosial.
Seperti komunitas sebelumnya Kelompok Sepuluh pun hanya seumur jagung. Kegiatan sastra hanya hidup di kampus-kampus dengan berbagai kegiatannya. Pada 1994, saya, Juniarso Ridwan, dan Agus R. Sardjono mendirikan Forum Sastra Bandung. Komunitas ini pun seperti komunitas lainnya perlahan surut, disebabkan aktivisnya mulai sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Seiring dengan itu di kampus-kampus selain ada Group Apresiasi Sastra (GAS) ITB, mulai pula muncul ASAS IKIP (UPI) Bandung dan beberapa komunitas lainnya, baik yang ada di Unpad dan beberapa universitas lainnya.
Kegiatan sastra yang dilakukan oleh komunitas-komunitas sastra di atas pada dasarnya lebih kepada acara mengundang orang untuk baca puisi, diskusi, dan menerbitkan buku. Sedangkan kegiatan yang membicarakan lahirnya kemungkinan daya estetik baru dalam penulisan karya sastra boleh dibilang tidak tersentuh. Hal ini saya sadari kemudian. Paling tidak, pada titik ini boleh dikatakan bahwa memikirkan gaya ucap baru, meskipun itu hanya berupa kelokan kecil atau jalan tikus dalam berproses kreatif, ternyata hanya dilakukan oleh masing-masing penyair yang tidak menyerah pada kehendak zaman untuk tidak berhenti menulis, apa pun hasilnya.
Dari generasi saya, misalnya, yang masih menulis adalah, Acep Zamzam Noor, Hikmat Gumelar, dan Nirwan Dewanto. Sedangkan dari Generasi Juniarso Ridwan, selain Juniarso Ridwan adalah Beni Setia dan Yessi Anwar. Demikian juga dengan generasi Nenden Lilis Aisyah, yang masih menulis adalah Matdon, Ahda Imran, Cecep Syamsul Hari, Eryandi Budiman, dan Mona Sylviana. Boleh jadi yang lainnya masih menulis, dan hal ini tidak terpantau oleh saya.
Tentu saja dalam perjalanannya lebih lanjut, perkembangan dan pertumbuhan kepenyairan di Bandung bukan hanya mereka yang saya sebutkan di atas. Ada generasi Yopi Umbara Putra, Ratna Ayu Budiarti, dan sederet nama lainnya, termasuk generasi Desiyanti Wirabrata dan Sinta Ridwan. Dalam konteks yang demikian itu, maka jelas sudah bahwa Bandung, besar atau kecil, telah menyumbangkan sesuatu bagi perkembangan dan pertumbuhan puisi Indonesia modern. Dan masalahnya sekarang adalah tinggal bagaimana kita melihat itu, dan mendudukkannya secara proporsional sehingga peta yang diharap bisa jelas adanya.***
* Tulisan ini merupakan makalah diskusi yang digelar oleh Majelis Sastra Bandung, di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu (25 Januari 2009)
Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »
11 Februari 2010
MEMBACA PAHLEVI, DAVE SKY, EMA, DAN DONI
Oleh : Heri Maja Kelana*
Belakangan ini saya senang memperhatikan tingkah orang-orang yang berada di sekitar tempat saya beraktivitas. Ternyata tingkah ternyata tingkah orang itu sangatlah beragam, walaupun keberagaman itu tidak lepas dari orang-orang sebelunya. Dalam bahasa Yasraf adalah meme (Genetik). Gen ini yang membuat sastra bertahan sampai sekarang. Bukan hanya itu, gen juga turun lewat bahasa. Bahasa tentunya tidak lepas dari konteks sosial dan kaidah yang sedang terjadi. Banyak sekali penyair yang mengeksplorasi bahasa, dari mulai Amir Hamzah, Chairil Anwar, Sutardji Calzoum Bachri, Afrizal Malna, sampai generasi sekarang yang ada di majelis sastra ini. Mereka mempunyai ciri dan identitas sendiri lewat bahasa yang dipakainya. Misalnya;
SANG HAI
ping diatas pong
pong diatas ping
ping ping bilang pong
pong pong bilang ping
mau pong? bilang ping
mau mau bilang pong
mau ping? bilang pong
mau mau bilang ping
ya pong ya ping
ya ping ya pong
tak ya pong tak ya ping
ya tak ping ya tak pong
kutakpunya ping
kutakpunya pong
pinggir ping kumau pong
pinggir pong kumau ping
tak tak bilang pong
sembilu jarakmu merancap nyaring
(sajak SANG HAI (1973), Sutardji Calzoum Bachri)
Walau bagaimanapun SANG HAI ini dikatakan sebuah puisi. Atau puisi Sitor Situmorang;
MALAM LEBARAN
bulan di atas kuburan
Ini juga sebuah puisi. Sebenarnya masih banyak lagi penyair yang mengksplorasi bahasa dan bentuk dalam karyanya. Bagi saya pribadi, penyair yang bermain dengan bahasa dan bentuk ini haruslah melalui tahap konvesional. Maksud saya begini, sebelum penyair bermain dengan bahasa dan bentuk, mereka harus tahu dan faham dengan bahasa dan bentuk itu sendiri. Walaupun keyakinan saya juga mengatakan pasti setiap penyair mempunyai konsep untuk menulis puisi. Apabila tidak mempunyia konsep, terkutuklah penair itu.
DENDAM
Bulan kini bertangiskan nanah
Para setanpun tertawa melihat diri ini tergeletak lemas
Kuteguk air penghangat
Dan ku teriakkan …………
Kuperintahkan untuk hancurkan
Hancurkan………….
Hancurkan………….
By. Reza
Bahasa adalah mendia untuk menulis karya sastra, terutama puisi. Pahlevi belum mampu memberikan satu diksipun kepada saya sebagai pembaca untuk dapat meningkatkan libido-libido sastra pada diri saya. Atrinya dalam segi bahasa belum ada kekuatan atau hal-hal yang ditawarkan kepada pembaca. Seharusnya Pahlevi harus suntuk dan khusuk lagi bergulat dalam bahasa.
SANG WAJAH
Cermin seperti berkaca
Makhluk apakah aku?
Cermin menangisi adanya
Melihat sang wajah suram
Kosong, penuh teka-teki
Haruskah dia memecahkan diri?
Muak dengan sang wajah,
Marah, benci
Dia tak bisa
Emosi itu bukan miliknya
Kata-kata bukan tuannya
Seringai sang wajah membuatnya tak berkutik
Bisakah dia memecahkan sang wajah?
(Sang Wajah, karya Ema)
Ema bermain pada logika bahasa. Ema juga membuat beberapa metafora, namun metafora-metafora yang diciptakan Ema belum kuat, “Sang Wajah” misalnya. Metafora “Sang Wajah” sudah menjadi metafora yang mati. Metafora yang mati ini maksudnya sudah menjadi konsumsi publik, seperti dalam bahasa sehari-hari, bahasa sinetron, dan lirik lagu. Sebenarnya sah-sah saja penyair membuat metafora yang sudah menjadi konsumsi publik atau yang sudah aus, bagi siapa saja yang ingin karyanya biasa-biasa saja.
TEH
rasa segala teh
dari teh terus teh terus lalu senin
selasa
rabu
kamis
jumat
sabtu
–
minggu,
dapatkah sisanya teh ?
(Teh, @dave sky)
Ada permainan bentuk yang ditawarkan oleh Dave Sky. Permainan bentuk ini mengingatkan saya pada puisi “WINKA SIHKA” Sutardji.
Tentang Rindu
kau berjalan seperti senja yang lupa mengeja
pasir dan langit.
di mana gadis cilik mengukir namanya di sana
langit menunggu senja membisik pasir
dan pasir menunggu langit menjabat senja
: inikah rindu itu?
Bogor, 210409
(Tentang Rindu, Doni P. Herwanto)
Doni telah berhasil mengubah pengalaman empirik menjadi larik-larik puitik. Walaupun secara tegas saya katakan bahwa konsep rindu yang ditawarkan doni belum berhasil. Saya tidak mendapatkan apa-apa dalam sajak ini. Doni harus lebih khusuk lagi mengakrabi tema-tema yang dibautnya.
Dari semuanya itu, saya pun memberikan suatu pandangan terhadap puisi yaitu teks hasil dari pengalaman hidup manusia yang diserap oleh organ tubuh, sehingga melahirkan suatu pemikiran yang baru. Pengalaman hidup manusia ini dibagi menjadi lima bagian yaitu;
Pengalaman empirik
Pengalaman empirik adalah pengalaman pribadi. Pengalaman ini menjadi pengalaman yang subjektif karena setiap orang memiliki pengalaman dan kadar rasa yang berbeda. Misalkan pengalaman putus cinta Amran dengan Utis akan berbeda, kadar kesakitannya pun akan berbeda.
Pengalaman Sosial
Pengalaman sosial adalah pengalaman hidup bermasyakat. Masyarakat ini tentunya berbeda, ada masyarakat kota dan desa. Kedua masyarakat itu mempunyai aktivitas yang berbeda, sehingga memberikan suatu pengalaman yang berbeda pula.
Pengalaman Mitos atau Legenda
Pengalaman mitos atau legenda ini akan menjadi refresentasi dari sebuah kebudayaan. Jawa Barat mempunyai legenda Sangkuriang dan Sumatra mempunyai legenda Malin Kundang, ditambah lagi dengan kekuatan-kekuatan orang-orang sakti yang bisa terbang atau menghilang. Secara langsung atau tidak langsung hal itu mempengaruhi pengalaman kita.
Pengalaman Sejarah
Pengalaman sejarah ini adalah pengalaman yang tidak pernah habis. Satu detik kebelakang adalah sejarah. Sejarah ini yang selalu menginspirasi penyair untuk menuliskan sebuah puisi.
Pengalaman Imajinasi
Pengalaman ini sangat berkaitan sekali dengan sastra. Ada yang dinamakan imaji yang liar dan imaji yang dangkal. Imajinasi juga bisa menjadi sebuah teknik untuk membuat sebuah karya (puisi).
Walau bagaimanapun saya memberikan satu apresiasai lebih terhadap Pahlevi, Dave Sky, Ema, dan Doni yang di zaman sekarang masih bisa menyempatkan menulis sastra. Terlepas dari karya sastra yang ditulisnya itu baik atau tidak. Seperti yang sudah saya tulis dari lima pengalaman hidup manusia di atas, keempat penyair ini mempunyai pengalaman dan ruang yang berbeda. Hal itu akan mempengaruhi terhadap karyanya. Modal terpenting adalah semangat, kemudian ditunjang dengan bahasa serta kepekaan seorang penyair terhadap lingkungan. Selamat berkarya kembali, begitupun dengan saya akan memperhatikan tingkah laku orang-orang di sekitar saya beraktivitas. Salam.
*penyair
Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »
 Kota Bandung memiliki banyak penyair muda potensial untuk melahirkan karya, sebagian mereka berkarya dengan cara bergerilya. Sebagian berhasil menembus dunia kepenyairan, namun sebagian besar gerilya para penyair muda ini tidak terlalu menggembirakan.
Kota Bandung memiliki banyak penyair muda potensial untuk melahirkan karya, sebagian mereka berkarya dengan cara bergerilya. Sebagian berhasil menembus dunia kepenyairan, namun sebagian besar gerilya para penyair muda ini tidak terlalu menggembirakan.
Banyak sebab, salah satu penyebabnya ialah ruang-ruang diskusi sastra yang sempat hidup pada tahun 80-90-an menjadi redup. Pun ketika menginjak tahun 2000-an, meski banyak komunitas yang mencoba eksis, tapi banyak yang mati suri.
Adalah penggiat sastra seperti Dedy Koral, Aendra Medita, Hermana HMT, Hanief, Ayi Kurnia, dan Yusef Muldiyana sepakat untuk mendirikan Majelis Sastra Bandung (MSB), dan melakukan aktivitas “Pengajian Sastra” dengan cita-cita menggali kembali gairah para penyair muda Bandung, menghidupkan kembali ruang-ruang diskusi yang pernah hidup beberapa waktu lalu.
Sebagaimana sebuah majelis (tempat duduk mencari ilmu), – katakanlah pengajian sastra menjadi tempat para penyair mengkaji ilmu dan pengetahuan tentang sastra yang di dalamnya meliputi puisi, novel, cerpen, teater, flm, musik dll.
Diakui atau tidak, selama ini para penyair muda kurang membaca karya orang lain, terlalu puas dengan satu kali berkarya, jarang mendiskusikan karya mereka, meskipun kini ada ruang teknologi yang begitu mudah untuk diakses baik dalam bentuk blog atau milis, jejaring Facebook dll, tapi semuanya itu tidak bisa mengalahkan ruang konvensional – bertatap muka – dialog.
Pada 25 januari 2009, bertempat di Gedung Indonesia Menggugat Bandung Jl. Perintis Kemerdekaan 5 Bandung, merupakan Launching MSB, diiawali dengan diskusi tentang “’Tradisi Sastra di Jawa Barat” menampilkan pembicara Hawe Setiawan dan Soni Farid Maulana.
Beberapa penyair “menghidupkan” Majelis ini, sebagian ada juga yang mempertanyakan dan meragukan keberadaan MSB, bahkan ada yang menuding MSB dibiayai oleh Partai Politik dan “diutus” pemerintah untuk memasuki wilayah sastra melalui para penggiatnya.
Entahlah, mungkin karena kepengurusan MSB memakai nama yang tak lazim dalam sebuah komunitas sastra. Di kepengurusan MSB ada Dewan Taqnin yang dipegang oleh Aendra H. Medita, Dewan Syuro Yusef Muldiyana dan Dedy Koral, Dewan Tanfidz Hermana HMT dan Hanief, sedangkan saya sebagai Rois ‘Am Majelis Sastra Bandung.
Istilah itu sebenarnya sama saja dengan Dewan penasehat, Dewan Musyawarah, Dewan pelaksana dan Ketua Umum.
Dari acara pengajian sastra, MSB sangat berharap para penyair muda mau berdarah-darah secara serius dan tidak pernah berhenti untuk berkarya, sebab seorang manusia akan diakui eksistensinya dengan berkarya.
Sebulan sekali MSB membahas-mendiskusikan karya para penyair muda, dipandu oleh para penyair yang lebih dulu mengenal dunia sastra, seperti Soni Farid Maulana, Hawe Setiawan, Syafrina Noorman, Imam Abda, Ahda Imran, Irfan Hidayatullah, Eriyanti Nurmala Dewi, Nenden Lilis Aisyah, Septiawan Santana, Anwar, Yopi Setia Umbara, Herri Maja Kelana, Anwar Kholid, Acep Zamzam Noor, dibantu beberapa anggota Forum Lingkar Pena (FLP) seperti seperti Adew Habtsa, Teni Indah, Ratna Ningsih dan Noel Saga. Pengajian Sastra ini terus berlangsung dengan aman, tertib dan sentosa.
Di antara hingar bingarnya sinisme dan cibiran terhadap MSB, akhirnya terbit juga antologi ini dengan kesederhanaan yang sangat sederhana. Sehingga kami bisa berkata bahwa MSB adalah sebuah lembaga kebudayaan (khususnya sastra) nirlaba, mengembangkan kesenian, penerbitan, penelitian, dokumentasi, dan wadah kreativitas tanpa dipengaruhi partai politik.
Terimakasih kepada semua rekan yang telah membantu MSB. Spesial terimakasih untuk Muhammad Safari Firdaus yang kerap hadir dan turut menghangatkan setiap pengajian, Ihung Chianda yang selalu mendukung moral MSB, kawan-kawan penyair yang sabar ikut memilih dan menyunting persiapan buku puisi ini seperti Wida Sireum Hideung, Semi Ikra Anggara, Hawe Setiawan, Adew Habtsa. Hanya Allah Swt yang akan mebalas kebaikan kalian.
Selamat berkarya kepada kawan-kawan penyair, ingat fatwa Majelis Sastra Bandung “Jangan pernah bercita-cita menjadi orang terkenal dalam berkarya. Sebab barang siapa yang berkarya – membuat puisi – karena ingin terkenal, maka Falyatabawwa Mak’adahu Minannar – bersiap siaplah masuk api neraka, artinya bersiap-siaplah untuk kecewa karena ternyata tidak terkenal”.
Berkaryalah dengan hati iklhlas!!
Bandung, Januari 2010
Matdon
(Rois ‘Am Majelis Sastra Bandung)
Ditulis dalam Uncategorized | Leave a Comment »